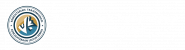Kadang, perjalanan bukan soal ke mana kita pergi, tapi bagaimana kita hadir. Bukan tentang tugas, tapi tentang niat. Rempang, dalam kunjungan ini, bukan sekadar lokasi di peta—ia menjadi ruang refleksi, tempat negara menguji keberpihakannya pada manusia.
Kunjungan kami ke Rempang di akhir Maret 2025 bukan hanya urusan birokrasi. Ia adalah perjalanan dari hati ke hati. Sebuah ikhtiar untuk hadir, bukan sekadar lewat tanda tangan dan berita acara, tapi lewat empati yang nyata, di antara suara-suara yang selama ini mungkin luput terdengar.
Hari Pertama – 29 Maret 2025
Pagi itu, kami terbang ke Batam. Setibanya di Bandara Hang Nadim, Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, disambut oleh Walikota Batam, Pak Amsakar Ahmad, dan Wakil Walikota, Bu Li Claudia Chandra. Tujuan pertama kami adalah TPS Buana Central Park, tempat puluhan kepala keluarga menunggu. Di sana, dialog terjadi bukan dari atas podium, tapi dari jarak yang manusiawi—duduk sejajar, mendengar satu per satu suara warga, tanpa naskah sambutan, tanpa formalitas yang kaku.
Pak Menteri datang bukan membawa janji, tapi waktu. Bukan pernyataan siap siar, tapi niat tulus untuk hadir dan mendengar. Bingkisan dari Presiden Prabowo Subianto diserahkan secara simbolik, sebagai tanda bahwa negara tak hanya hadir untuk mereka yang setuju relokasi, tapi juga untuk yang menolak—semua didengar, semua dihormati.
Dari TPS, perjalanan berlanjut ke Pulau Rempang. Di Rempang Eco Park, Pak Menteri memutuskan untuk menginap di rumah hunian calon transmigran. Keputusan itu sederhana, tapi dalam. Ia ingin benar-benar merasakan denyut kehidupan yang sedang tumbuh, tidur di tempat yang sama, makan bersama, dan mengalami sendiri suasana yang tengah dibangun sebagai awal baru.
Sore menjelang malam, kami tiba di Kampung Pasir Merah. Sebuah kawasan di mana sebagian warga dengan tegas menolak relokasi. Aksi penolakan berlangsung terbuka saat kami datang. Tapi Pak Menteri dan jajaran, termasuk Pak Walikota dan Wakil Walikota Batam, tidak menghindar. Mereka turun dari mobil, menghampiri para pendemo, dan berkata pelan tapi tegas: “Kami hadir untuk mendengar.” Tidak semua keluhan bisa langsung dijawab hari itu. Tapi satu hal yang pasti: semuanya dicatat, dan semuanya diterima dengan penuh hormat.
Malamnya, kami berbuka puasa bersama Wakil Walikota Batam di sebuah restoran seafood sederhana di Pulau Rempang. Makanannya enak, suasananya hangat. Setelah itu, Pak Menteri berdialog dengan jurnalis dan menggelar briefing internal di rumah hunian tempat beliau menginap. Hari pertama ditutup dengan kesederhanaan, tapi juga ketulusan.
Hari Kedua – 30 Maret 2025
Pukul 04.30 pagi, Pak Menteri sudah bersiap menuju Masjid di Pasir Merah untuk sholat subuh berjamaah. Usai ibadah, beliau kembali ke Eco Park. Suasana pagi mulai hidup. Beberapa warga sudah memulai aktivitas, termasuk berkebun hidroponik. Ada kehidupan yang tumbuh, dan ada semangat yang tak bisa disembunyikan—semacam harapan baru yang sedang dicoba dirajut pelan-pelan.
Setelah berganti pakaian, kegiatan dilanjutkan dengan dialog bersama warga calon transmigran, disusul pemotongan sapi dan penyerahan bingkisan dari Presiden. Siang harinya, kami bersama Ibu Wakil Walikota yang setia terus mendampingi kegiatan kami, berkunjung ke Kampung Pasir Panjang. Di aula masjid, Pak Menteri kembali duduk melantai bersama warga. Tidak untuk membujuk. Tapi untuk membuka ruang percakapan yang jujur dan sejajar.
“Transmigrasi bukan paksaan,” ujar beliau. “Kalau ada warga yang digusur secara paksa, saya sendiri yang akan berdiri paling depan untuk membela mereka.” Di hadapan warga yang skeptis, pernyataan itu bukan sekadar pembelaan. Ia adalah penegasan bahwa negara tak boleh hadir dengan kekuasaan saja, tapi dengan keberpihakan yang manusiawi.
Pulau Galang dan Refleksi
Menjelang sore, rombongan melanjutkan perjalanan ke Pulau Galang. Di pulau kecil ini pernah berdiri kamp pengungsian besar bagi 250 ribu warga Vietnam antara tahun 1979 hingga 1996. Jejak-jejak kemanusiaan masih terasa.
Di sana, Pak Menteri berdiri diam sejenak. Lalu berujar, “Tempat ini mengingatkan kita, bahwa jika kerukunan tidak dijaga, maka konflik bisa terjadi. Dan dari konflik, bisa lahir gelombang pengungsi. Bahkan di tanah sendiri.” Kalimat itu sederhana, tapi membawa bobot sejarah yang tak ringan. Karena pembangunan yang terburu-buru, tanpa dialog dan kepekaan, bisa melahirkan luka yang lama sembuhnya.
Malam Menjelang Lebaran
Pak Menteri bersilaturahmi ke kediaman Bapak Yan Fitri, tokoh Batam dan mantan Kapolda Kepri. Kami berbuka puasa bersama di malam terakhir Ramadhan, lalu bergabung dalam pawai takbir yang diadakan Pemkot Batam. Kota menyambut hari kemenangan dengan semarak. Tapi di balik perayaan itu, ada perenungan yang dalam tentang keadilan dan kehadiran negara.
Malam itu ditutup dengan sesi makan durian di teras rumah hunian transmigran. Obrolan mengalir ringan bersama jurnalis dan jajaran dari Jakarta. Tidak ada protokol. Hanya manusia bertemu manusia.
Hari Ketiga – 31 Maret 2025 (1 Syawal 1446 H)
Pagi hari, Pak Menteri sholat Ied di Masjid Pasir Merah. Duduk sejajar dengan warga yang kemarin masih berdemonstrasi. Tidak ada garis batas. Tidak ada dikotomi antara “yang setuju” dan “yang menolak.” Hanya umat yang sedang berdoa bersama.
Setelah itu, beliau kembali ke Eco Park, bersilaturahmi dan makan opor bersama keluarga calon transmigran. Dalam suasana lebaran yang syahdu, beliau menyampaikan, “Saya ingin merasakan roso, jiwa, soul yang dirasakan masyarakat Rempang saat merayakan Idul Fitri ini. Dan saya juga ingin meminta maaf kepada warga Rempang atas langkah-langkah pemerintah yang mungkin pernah menyakitkan.”
Kami menutup perjalanan ini dengan menghadiri open house di rumah dinas Walikota Batam. Dalam perjalanan, Pak Menteri tetap membuka waktu untuk wawancara dengan jurnalis. Tidak lelah. Tidak tertutup. Karena bagi beliau, mendengar adalah bagian dari pekerjaan.
Refleksi Akhir
Rempang bukan hanya nama pulau. Bukan pula sekadar tanah seluas 17.000 hektare yang dihuni 2.637 kepala keluarga. Ia adalah suara. Ia adalah doa yang menunggu dikabulkan. Ia adalah harapan bahwa pembangunan tidak semestinya menjadi alat pemaksaan, melainkan jalan menuju keadilan.
Di Rempang, tak ada SMA. Apalagi perguruan tinggi. Di antara suara-suara yang menyambut relokasi dengan hati terbuka, ada satu hal yang terus disuarakan: masa depan.
“Saya nelayan. Saya sadar, kalaupun nanti ada industri di Rempang, saya mungkin tetap jadi nelayan, atau paling banter buruh pabrik. Tapi saya ingin anak saya bisa sekolah tinggi. Saya ingin di Rempang nanti ada SMA dan perguruan tinggi. Supaya anak-anak kami bisa belajar, lalu bekerja di tanah sendiri. Jadi mandor, atau bahkan pimpinan di industri itu. Jangan seperti tetangga saya—anaknya sekolah tinggi ke luar Rempang, lalu tak pernah kembali, karena di sini tak ada pekerjaan yang bisa menampung mereka. Anak-anak kami tak bisa hidup seperti kami. Mereka tak mungkin selamanya mengandalkan laut dengan cara tradisional.”
Tiga hari di Rempang memang singkat. Tapi maknanya akan tinggal lama. Karena perubahan besar sering kali dimulai dari satu hal yang sederhana: keberanian untuk hadir, dan kerendahan hati untuk benar-benar mendengar.
Penulis adalah Tenaga Ahli Menteri Transmigrasi (Yoyo Budianto) yang mengikuti rangkaian perjalanan Mentrans ke Rempang